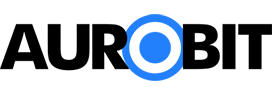Lahan dan Pengembangan: Menyelesaikan Konflik
Daftar Isi
Pentingnya Kebijakan Satu Peta
Kebijakan Satu Peta (Kebijakan Satu Data Satu Peta) merupakan upaya pemerintah untuk menyatukan data dan informasi geospasial di Indonesia. Sebelum ada kebijakan ini, berbagai data geospasial yang dimiliki oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) tumpang tindih dan saling bertentangan, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih lahan dan konflik lahan di berbagai wilayah.Kondisi Sebelum Kebijakan Satu Peta
Sebelum diberlakukannya Peraturan Presiden No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, masing-masing Kementerian, Lembaga, dan Pemda memiliki data, peta, dan informasi geospasial yang saling tumpang tindih. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik pemanfaatan lahan dan tumpang tindih perizinan di berbagai daerah.Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan geoportal KSP sebagai pusat informasi data geospasial terpadu. Geoportal ini menjadi platform yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan data dan informasi geospasial yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik lahan.Contoh Konflik Lahan di Provinsi Riau
Provinsi Riau, yang terletak di Pulau Sumatera, menjadi contoh nyata bahwa konflik lahan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara komprehensif. Tiga kasus konflik lahan di Riau ini menunjukkan bahwa Kebijakan Satu Peta (KSP) masih perlu ditingkatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa terkait pemanfaatan lahan di wilayah tersebut.Konflik Batas Desa
Di Provinsi Riau, sering terjadi konflik batas desa yang disebabkan oleh kurangnya kejelasan informasi terkait batas-batas administratif wilayah. Hal ini menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan antara masyarakat desa yang berbatasan. Konflik batas desa ini dapat menghambat pembangunan dan pengembangan wilayah, serta mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan lahan di Provinsi Riau.Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan
Selain itu, konflik lahan juga terjadi antara masyarakat dengan pemilik perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan lahan, sehingga menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan antara masyarakat setempat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.Konflik dengan Masyarakat Adat
Selain kasus di atas, konflik lahan juga terjadi antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang mengklaim penguasaan atas lahan yang dianggap sebagai wilayah adat. Permasalahan ini menjadi kompleks karena melibatkan status hukum dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di Provinsi Riau.Menariknya, Presiden Jokowi berseloroh bahwa banyak pihak yang takut jika KSP dilaksanakan. Namun, tiga contoh konflik lahan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa KSP masih perlu ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik lahan yang ada.Kebutuhan Peta untuk Penyelesaian Konflik
Melihat model-model kasus tersebut, penyelesaian peta batas desa, peta perkebunan rakyat, peta potensi wilayah adat, dan peta perhutanan sosial menjadi sangat penting untuk mencapai mimpi Kebijakan Satu Peta (KSP). Sayangnya, 3 peta terakhir belum menjadi peta tematik prioritas dalam KSP. Bahkan, seluruh peta dalam geoportal KSP belum dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah perlu memberikan akses masyarakat agar dapat dimanfaatkan langsung dalam penyelesaian konflik lahan bersama masyarakat.Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah
Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku ketua pelaksana Kebijakan Satu Peta (KSP) menekankan pentingnya peran Pemda sebagai simpul jaringan dalam pelaksanaan KSP. Contohnya, Pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki Peraturan Gubernur No. 5/2019 tentang Satu Data Satu Peta, unit pengelola informasi geospasial, dan geoportal yang terkoneksi ke pusat. Namun, model-model kasus di Riau menegaskan bahwa Pemda perlu terlibat sampai ke tingkat tapak, misalnya menjadi mediator antara 2 desa yang bersengketa batas.Pelembagaan Resolusi Konflik Multi-Pihak
Tim Kerja Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat yang dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di Provinsi Sumatera Selatan, serta Tim Penanganan Konflik Sumber Daya Alam di Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi contoh bagaimana resolusi konflik diupayakan melalui pendekatan kelembagaan. Kedua tim ini terdiri dari perwakilan berbagai instansi, seperti Pemda tingkat Provinsi atau Kabupaten, KPH, dan lembaga swadaya masyarakat.Sedangkan di Riau, Pokja PPS mulai digencarkan melalui revisi SK Gubernur. Hal ini menunjukkan upaya pelembagaan resolusi konflik yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan.Dukungan Universitas dalam Peningkatan Kapasitas SDM
Kebutuhan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama lambatnya progres Kebijakan Satu Peta (KSP). Aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki kemampuan teknis pemetaan umumnya hanya ditemukan pada instansi tertentu seperti; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Universitas di daerah dapat berkontribusi melalui kegiatan pelatihan, penelitian dan pelibatan mahasiswanya.Contohnya, Universitas Riau bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengerahkan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk melaksanakan pemetaan desa secara partisipatif di salah satu kecamatan. Hasilnya, mahasiswa membantu mendorong kesepakatan pada 7 dari 13 segmen batas desa.keabsahan tanah pembangunan hunian
Kesesuaian lahan pembangunan hunian dengan rencana tata kota dan perizinan, serta kejelasan status kepemilikan lahan adalah kunci untuk menghindari konflik pertanahan. Dengan adanya sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, dan dokumen akta jual beli, dapat memberikan kepastian penguasaan lahan bagi pembangunan hunian.Pentingnya Kejelasan Status Kepemilikan Lahan
Kejelasan status kepemilikan lahan, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, dan data pertanahan lainnya, sangat penting untuk memastikan lahan yang digunakan untuk pembangunan hunian benar-benar milik pemilik yang sah. Hal ini akan menghindari potensi konflik pertanahan di kemudian hari.Proses Perizinan Pembangunan Hunian
Selain kejelasan status kepemilikan lahan, proses perizinan pembangunan hunian juga harus diperhatikan. Hal ini meliputi izin mendirikan bangunan (IMB) yang harus sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah setempat. Dengan memenuhi seluruh persyaratan perizinan, pembangunan hunian dapat dilaksanakan secara legal dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.Pelibatan Masyarakat untuk Pemetaan Partisipatif
Masyarakat lokal merupakan pengelola langsung kawasan tempat mereka tinggal, sehingga paham mengenai semua potensi di sekitarnya. BIG memfasilitasi penyelenggaraan pemetaan partisipatif berbasis masyarakat lokal melalui aplikasi PetaKita. Aplikasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan di wilayah yang tidak terjangkau internet. Selanjutnya, hasil pemetaan partisipatif dapat Pemda sesuaikan untuk kebutuhan Kebijakan Satu Peta (KSP).Strategi Penyelesaian Konflik Lahan
Penyelesaian Melalui Mediasi dan ADR
Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. Saat ini telah lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR), salah satunya dengan menggunakan mediasi. Masyarakat juga dapat melibatkan seorang pekerja sosial dalam membantu menyelesaikan konflik/sengketa lahan yang sedang dihadapi.Peran Pekerja Sosial dalam Resolusi Konflik
Pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses resolusi konflik, seperti menjadi Negosiator ataupun Mediator. Melalui mediasi dan pendekatan ADR, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik lahan yang berkelanjutan.Harmonisasi Regulasi dan Koordinasi Antar Lembaga
Penyelesaian konflik agraria dan kawasan hutan memerlukan koordinasi lintas sektor antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain itu, juga perlu dilakukan harmonisasi peraturan untuk menghindari terjadinya disharmonisasi antar regulasi yang ada. Hal ini penting agar peraturan yang telah dibuat segera diimplementasikan dan dipahami oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga dapat menghindari kesalahan penafsiran regulasi.Misalnya, terkait penguasaan lahan di kawasan hutan, harus ada kejelasan mengenai peraturan dan pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan. Begitu pula dengan perizinan pembangunan yang harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Koordinasi dan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga terkait sangat diperlukan agar dapat mencegah dan menyelesaikan konflik lahan yang sering terjadi.
Kesimpulan
Untuk menghindari konflik pertanahan, kesesuaian lahan pembangunan hunian dengan rencana tata kota dan perizinan, serta kejelasan status kepemilikan lahan adalah kunci utama. Selain itu, peran aktif lembaga pemerintah, koordinasi lintas sektor, dan harmonisasi regulasi juga penting dalam menyelesaikan konflik lahan di Indonesia.Pemerintah daerah sebagai simpul jaringan pelaksana Kebijakan Satu Peta (KSP) perlu terlibat hingga tingkat tapak, misalnya menjadi mediator antara desa yang bersengketa. Selain itu, dukungan akademisi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemetaan partisipatif masyarakat lokal dapat mendorong percepatan penyelesaian konflik lahan.Resolusi konflik juga dapat ditempuh melalui mediasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR), dengan melibatkan pekerja sosial sebagai negosiator atau mediator. Harmonisasi peraturan serta koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait juga diperlukan untuk menghindari disharmonisasi regulasi dalam penyelesaian konflik agraria dan kawasan hutan.FAQ
Apa yang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan dan konflik lahan di Indonesia sebelum adanya Kebijakan Satu Peta (KSP)?
Sebelum ada Kebijakan Satu Peta (KSP), Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki data, peta, dan informasi geospasial masing-masing. Hal ini mengakibatkan sering terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dan konflik lahan di Indonesia.
Bagaimana dampak positif yang diharapkan dari pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)?
Dengan adanya Kebijakan Satu Peta (KSP), diharapkan dapat menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan konflik lahan yang sering terjadi di Indonesia. KSP akan menyatukan data, peta, dan informasi geospasial dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Apa saja contoh konflik lahan yang terjadi di Provinsi Riau dan bagaimana penyelesaiannya?
Tiga contoh konflik lahan di Provinsi Riau yang menunjukkan bahwa KSP masih perlu ditingkatkan untuk menyelesaikan konflik lahan yang ada, yaitu: konflik batas desa, konflik perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, dan konflik dengan masyarakat adat. Penyelesaian konflik-konflik tersebut membutuhkan peta-peta tematik seperti Peta Batas Desa, Peta Perkebunan Rakyat, Peta Potensi Wilayah Adat, dan Peta Perhutanan Sosial.
Mengapa peta-peta tematik seperti Peta Batas Desa, Peta Perkebunan Rakyat, Peta Potensi Wilayah Adat, dan Peta Perhutanan Sosial penting untuk mencapai tujuan Kebijakan Satu Peta (KSP)?
Peta-peta tematik tersebut penting untuk menyelesaikan konflik lahan yang ada di Indonesia. Namun, 3 peta terakhir belum menjadi peta tematik prioritas dalam KSP. Selain itu, seluruh peta dalam geoportal KSP juga belum dapat diakses oleh masyarakat. Akses masyarakat terhadap peta-peta tersebut sangat penting untuk penyelesaian konflik lahan bersama masyarakat.
Bagaimana peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)?
Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku ketua pelaksana KSP menekankan pentingnya peran Pemda sebagai simpul jaringan dalam pelaksanaan KSP. Contohnya, Pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki Peraturan Gubernur No. 5/2019 tentang Satu Data Satu Peta, unit pengelola informasi geospasial, dan geoportal yang terkoneksi ke pusat. Namun, Pemda juga perlu terlibat sampai ke tingkat tapak, misalnya menjadi mediator antara 2 desa yang bersengketa batas.
Bagaimana resolusi konflik lahan dapat diupayakan melalui pendekatan kelembagaan?
Tim Kerja Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat yang dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di Provinsi Sumatera Selatan, serta Tim Penanganan Konflik Sumber Daya Alam di Kabupaten Musi Banyuasin, dapat menjadi contoh bagaimana resolusi konflik diupayakan melalui pendekatan kelembagaan. Kedua tim ini terdiri dari perwakilan berbagai instansi, seperti Pemda tingkat Provinsi atau Kabupaten, KPH, dan lembaga swadaya masyarakat.
Bagaimana peran Universitas dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)?
Universitas di daerah dapat berkontribusi melalui kegiatan pelatihan, penelitian dan pelibatan mahasiswanya. Contohnya, Universitas Riau bekerja sama dengan BIG dan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengerahkan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk melaksanakan pemetaan desa secara partisipatif di salah satu kecamatan.
Apa yang menjadi kunci untuk menghindari konflik pertanahan dalam pembangunan hunian?
Kesesuaian lahan pembangunan hunian dengan rencana tata kota dan perizinan, serta kejelasan status kepemilikan lahan adalah kunci untuk menghindari konflik pertanahan. Dengan adanya sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, dan dokumen akta jual beli, dapat memberikan kepastian penguasaan lahan bagi pembangunan hunian.
Bagaimana peran masyarakat lokal dalam pemetaan partisipatif untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP)?
Masyarakat lokal merupakan pengelola langsung kawasan tempat mereka tinggal, sehingga paham mengenai semua potensi di sekitarnya. BIG memfasilitasi penyelenggaraan pemetaan partisipatif berbasis masyarakat lokal melalui aplikasi PetaKita. Hasil pemetaan partisipatif ini dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk kebutuhan KSP.
Bagaimana strategi penyelesaian konflik lahan selain melalui jalur litigasi?
Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. Saat ini telah lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR), salah satunya dengan menggunakan mediasi. Masyarakat juga dapat melibatkan seorang pekerja sosial dalam membantu menyelesaikan konflik/sengketa lahan yang sedang dihadapi.
Apa yang perlu dilakukan untuk harmonisasi regulasi dan koordinasi antar lembaga dalam menyelesaikan konflik lahan?
Penyelesaian konflik agraria dan kawasan hutan perlu dilakukan koordinasi antar kementerian/lembaga. Selain itu, juga perlu dilakukan harmonisasi peraturan untuk menghindari terjadinya disharmonisasi antar regulasi yang ada, agar segera diimplementasikan dan dipahami oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghindari kesalahan penafsiran regulasi.